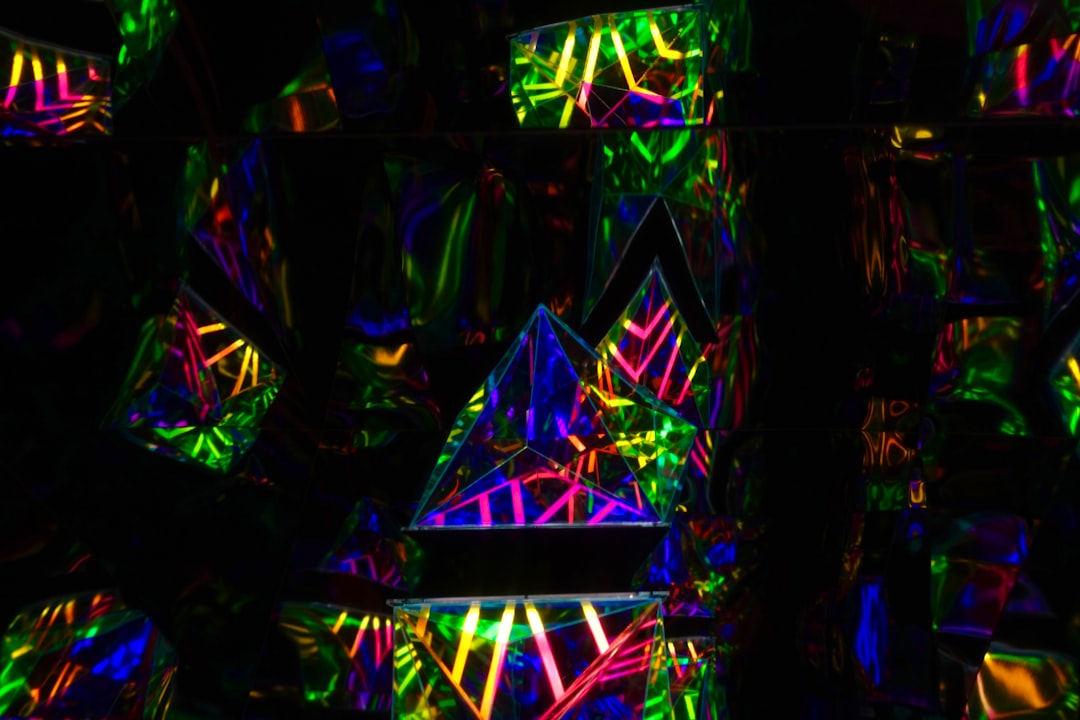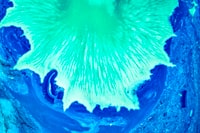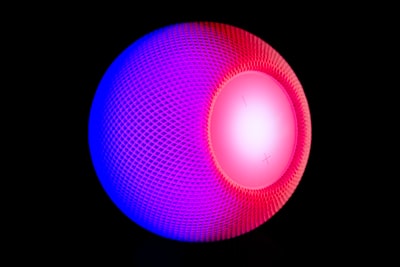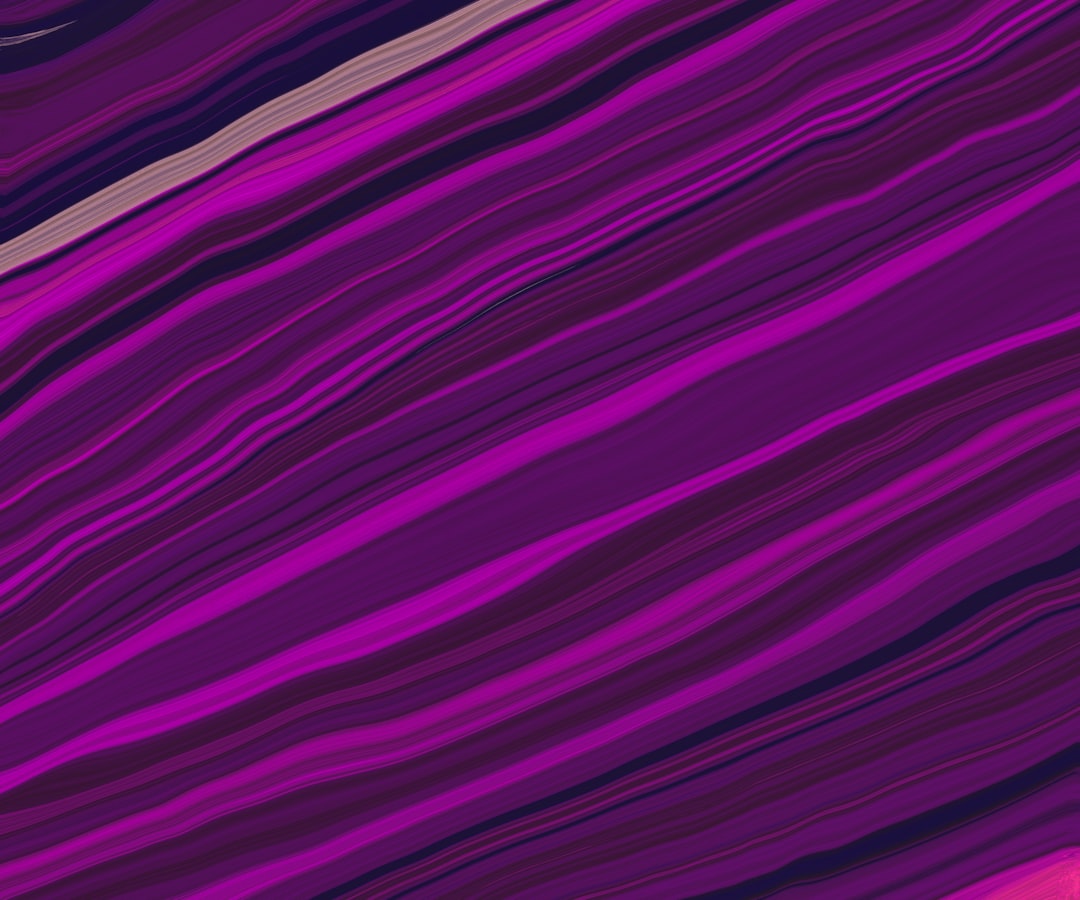Journal article
Diskursus tentang perencanaan dan pengembangan wilayah di Indonesia menjadi semakin menarik setalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pemberlakuan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka berbagai daerah menuntut pemekaran wilayah yang berlansung secara massif. Namun, realitas menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan pemekaran, sesungguhnya tidak didasari pada ide dan gagasan substansi dari pemekaran wilayah itu sendiri. Kondisi ini terlihat jelas dengan jalur yang ditempuh dalam mendorong gagasan pemekaran wilayah lebih mempertimbangkan aspek politik daripada aspek substansinya. Dalam kajian ilmu perencanaan dan pengembangan wilayah, kebijakan otonomi daerah memiliki semangat untuk membangun keberimbangan pembangunan antar wilayah atau desa-kota. Keberimbangan pembangunan yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam, manusia, sosial dan buatan) akan terdistribusi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa tujuan luhur pemekaran wilayah seringkali mengalami kesalahan pemaknaan, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat mengalami kemandekan, bahkan cenderung gagal total. Hal ini sebagaimana dijelaskan, Juanda (2008) bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Namun pemekaran juga seringkali menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, keuangan dan kemampuan bertahan dalam perkembangannnya, sehingga menyebabkan kontra-produktif terhadap otonomi daerah. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah harus mengedepankan aspek-aspek normatif yang telah dirumuskan, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun peraturan pemerintah tentang syarat-syarat pemekaran wilayah. Namun hal penting yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pemekaran wilayah adalah aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk turut serta dipertimbangkan sehingga protes dan atau resistensi penolakan warga pasca pemekaran atau penggabungan wilayah yang seringkali menghiasi daerah-daerag pemekaran dapat dihindarkan. Sebab, fakta menunujukkan berbagai protes dan penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat atas ide pemekaran maupun penggabungan wilayah diberbagai daerah akibat dari proses pemekaran wilayah didominasi oleh elite atau kelompok-kelompok tertentu tanpa melibatkan peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif. Fenomena pemekaran dan penggabungan wilayah yang mengakibatkan penolakan warga masyarakat akibat dari pengabaian aspiarasi masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara. Kasus ini terjadi pada masyarakat enam desa sengketa yang diperebutkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada saat ini. Penolakan warga masyarakat enam desa atas gagasan pemekaran dan penggabungan wilayah lebih disebabkan aspirasi masyarakat enam desa yang sejak awal menolak untuk menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Malifut dipaksakan oleh pemerintah untuk tetap menjadi bagian dari Kecamatan Malifut yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999. Penolakan ini juga didasari oleh berbagai alasan, diantaranya adalah kedekatan emosional, historis dan identitas wilayah. Dimana wilayah enam desa, sebelum keluar PP Nomor 42 Tahun 1999 merupakan bagian wilayah administratif Kecamatan Jailolo, sehingga dari sisi kedekatan emosional dan historis, masyarakat di wilayah enam desa menganggap bahwa daerah ini (baca: enam desa) dibesarkan oleh jailolo sehingga harus tetap menjadi bagian dari Kecamatan Jailolo yang selanjutnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana dijelaskana sebelumnya, bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunanan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun sesame pemerintah daerah. Namun, harus jujur dikatakan bahwa gagasan luhur pemekaran wilayah sebagaimana diatas, terkadang tercoreng oleh adanya arogansi pemerintah daerah. Hal tersebut, dapat terlihat pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, se-misal konflik batas wilayah, penguasaan sumberdaya alam antar sesama pemerintah daerah yang banyak belum terselesaikan. Kelambanan ini dikarenakan lemahnya pengambilan keputusan pada level elite lokal (baca: Gubernur) yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, juga dikarenakan proses penyelesaian berbagai permasalahan ini lebih dominan menggunakan pendekatan politik, sehingga terdapat pihak yang dikorbankan. Pada aras ini rakyatlah yang kemudian menjadi korban dari ketidak-bijaknya para elite-elite kekuasaan di daerah. Menurut PP nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, tujuan pemekaran adalah memaksimalkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendemokratisasi masyarakat, efisiensi pemerintahan dan dukungan pembangunan potensi ekonomi rakyat. Namun dalam implementasinya, berbagai tujuan mulia tersebut belum tercapai secara maksimal. Hal mana dapat dilihat pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahaan di daerah-daerah yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri akhir tahun 2005, yang menjelaskan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah pemekaran belum menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum pemekaran (Laporan Depdagri, 2006; Dikutip Malia 2009). Kenyataan tersebut selain disebabkan oleh beberapa kendala tekhnis administrasi dan fasilitas pendukung pelayanan yang belum memadai, juga terbatasnya komitmen pimpinan daerah untuk menciptakan sistem dan pelaksanaan pelayanan publik yang transparan, accountable, dan professional. Sebenarnya banyak aspek yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan pemekaran wilayah, namun sepertinya motivasi kalkulasi secara politik yang seringkali menjadi alasan dominan. Bahkan tak jarang persetujuan terhadap adanya pemekaran wilayah diberikan untuk meredam konflik. Hal lainnya adalah otonomi seringkali menjadi suatu komoditas yang bisa diperdagangkan untuk memberikan kekuasaan pada daerah tertentu. Meskipun tidak semua kasus, namun pada beberapa kasus pemekaran wilayah, memang benar menjadi tuntutan masyarakat akan perlunya otonomi daerah, tetapi tetap saja, pada faktanya kaum elite di daerah yang diuntungkan. Dan implikasi lanjutannya adalah masyarakat tidak pernah menjadi sejahtera serta perkembangan ekonomi wilayahpun menjadi tersendat-sendat (Sayori, 2009)